Di tengah hiruk-pikuk ekonomi digital, kondisi pengemudi ojek online (ojol) kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, polemik yang muncul adalah tentang apakah ojol berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) atau tidak. Apalagi ketika beberapa serikat/organisasi ojol yang secara aktif melakukan aksi protes menuntut THR banyak diliput oleh berbagai media.
Alih-alih mendapatkan dukungan, tidak sedikit pihak—termasuk dari kalangan organisasi ojol—yang justru mempertanyakan tuntutan tentang THR ini. Argumen utama yang menolak tuntutan ini, secara umum, berpijak pada pendekatan legalistik: karena tidak ada aturan yang mewajibkan platform digital memberikan THR kepada mitra, maka tuntutan ini dianggap tidak logis.
Namun, jika kita melampaui tafsir legalisme sempit dan memeriksa lebih dalam hubungan kerja dalam ekonomi gig, maka tuntutan THR bagi ojol bukan hanya wajar, tetapi juga logis—dalam kerangka keadilan sosial dan prinsip kemitraan yang sejati.
Pendekatan Legalistik: Keterbatasan dalam Memahami Realitas Kerja Ojol
Pendekatan yang menolak tuntutan THR bagi ojol sering kali bersandar pada positivisme hukum, di mana hak dan kewajiban pekerja hanya diakui jika telah tertulis dalam regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, THR dianggap sebagai hak yang hanya diberikan kepada pekerja formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 dan UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur bahwa THR wajib diberikan kepada pekerja dengan hubungan kerja berbasis perjanjian kerja yang sah atau pekerja formal.
Sementara itu, pengemudi ojol secara legal dikategorikan sebagai “mitra” platform, bukan pekerja. Dengan status ini, maka diklaim bahwa pekerja gig (termasuk pengemudi ojol) tidak berhak atas tunjangan atau hak-hak lain yang dinikmati pekerja formal, termasuk THR. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi perusahaan platform untuk memberikan THR kepada pengemudi.
Pandangan ini didasarkan pada pendekatan legalis yang menganggap aturan yang tertulis sebagai batasan mutlak dari apa yang bisa atau tidak bisa dituntut. Jika hukum tidak mengatur sesuatu, maka itu dianggap di luar ruang legitimasi tuntutan. Pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar karena gagal memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan refleksi dari dinamika sosial yang selalu berkembang.
Dalam konteks ekonomi digital, hubungan kerja tidak selalu dapat dikotak-kotakkan dalam klasifikasi lama: pekerja versus pemberi kerja. Platform digital sering kali beroperasi dalam wilayah abu-abu, di mana mereka menolak tanggung jawab sebagai pemberi kerja tetapi tetap mengontrol aspek-aspek fundamental dari pekerjaan mitra mereka—mulai dari sistem insentif, algoritma yang menentukan order dan sanksi bagi ojol, hingga pengaturan proses kerja yang memengaruhi pendapatan pengemudi. Ketidakseimbangan kekuatan ini mencerminkan bahwa hubungan yang disebut sebagai “kemitraan” sering kali lebih menyerupai hubungan kerja terselubung (disguised wage labour).
Subscribe untuk mendapatkan update informasi dari arifnovianto.id
Memaknai Kemitraan secara Kritis
Jika kita kembali kepada konsep kemitraan yang sejati, salah satunya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka hubungan kemitraan seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan, tidak ada yang menguasai dan dikuasai, serta keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dengan kata lain, dalam hubungan yang benar-benar berbasis kemitraan, ojol tidak berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding platform. Mereka memiliki hak suara yang sama dalam menentukan aspek-aspek kerja dan bagi hasil.
Namun, dalam praktiknya, konsep kemitraan ini sering kali hanya menjadi formalitas. Perusahaan platform memiliki kontrol yang jauh lebih besar dibandingkan pengemudi, sehingga posisi antar-pihak yang bermitra menajdi tidak setara. Algoritma platform menentukan berbagai hal dalam proses kerja, yang dalam banyak kasus telah memaksa pengemudi ojol untuk bekerja secara berlebihan (rata-rata di atas 13 jam per hari). Dalam konteks ini, relasi yang terjadi lebih menyerupai hubungan kerja (ada atasan-bawahan, yang memerintah-diperintah) ketimbang kemitraan sejajar.
Jika kita berpegang pada esensi kemitraan, maka pengemudi ojol memiliki hak untuk mendiskusikan pengaturan kerja dan bagi hasil, termasuk menuntut THR. Sebagaimana dalam kemitraan bisnis lainnya, pihak-pihak yang bermitra dapat melakukan negosiasi untuk menentukan kompensasi yang adil. Jika platform menganggap pengemudi sebagai mitra sejati, maka tuntutan THR bukanlah sesuatu yang tidak logis, melainkan bagian dari hak pengemudi untuk berunding dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Melampaui Formalisme Hukum
Dalam sistem ekonomi digital yang semakin berkembang, hukum sering kali tertinggal dari realitas sosial. Oleh karena itu, tuntutan THR bagi ojol tidak dapat dinilai hanya dari perspektif legalisme sempit. Menolak tuntutan THR dengan alasan formalisme hukum, dalam perspektif humanis, sama artinya dengan mengabaikan prinsip keadilan bagi pekerja dan dinamika yang berkembang dalam ekonomi digital. Ada beberapa alasan mengapa tuntutan THR bagi ojol masuk akal dan wajar:
1. Pengemudi Ojol Berkontribusi Sepanjang Tahun
Setiap tahun, pengemudi ojol bekerja tanpa jaminan pendapatan tetap, menghadapi fluktuasi tarif yang sering kali merugikan mereka, serta harus menanggung sendiri biaya operasional sarana kerja (kendaraan, HP, dll). Jika pekerja formal mendapatkan THR sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka selama satu tahun, maka wajar jika pengemudi ojol juga mengajukan tuntutan yang serupa. Apalagi, kondisi kerja pengemudi ojol saat ini jauh lebih rentan dibanding pekerja formal.
2. Pola Kerja Ojol Semakin Menyerupai Pekerjaan Formal
Banyak pengemudi ojol yang bekerja penuh waktu, bergantung sepenuhnya pada penghasilan dari platform, dan mengikuti berbagai kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Pada konteks ini, aspek dalam hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan, perintah, dan upah menjadi semakin kentara. Akibat berbagai kontrol kerja, telah membuat kondisi kerja pengemudi menyerupai kondisi kerja para pekerja formal. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan untuk mendapatkan THR menjadi semakin masuk akal.
3. Negosiasi Kolektif sebagai Hak Mitra
Sebagai mitra, pengemudi ojol memiliki hak untuk bersuara dan bernegosiasi dengan platform mengenai hak-hak mereka. Jika perusahaan benar-benar menganggap pengemudi ojol sebagai mitra sejajar, maka mereka harus bersedia mendengarkan dan merundingkan tuntutan yang diajukan oleh pengemudi, misalnya tuntutan THR. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan sebagai aktor yang memastikan bahwa proses negosiasi berjalan secara adil dan tidak timpang dengan mengutamakan keberpihakan kepada kelompok yang rentan, yaitu ojol.
4. Preseden di Negara Lain
Beberapa negara telah mulai memberikan perlindungan lebih bagi pekerja gig, termasuk hak-hak yang sebelumnya hanya dinikmati oleh pekerja formal. Misalnya, di beberapa bagian Eropa, pengemudi layanan transportasi daring mulai mendapatkan pengakuan sebagai pekerja dengan hak atas upah minimum dan tunjangan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi bisa berkembang seiring dengan perubahan ekosistem kerja.
THR sebagai Kemenangan Kecil menuju Kemenangan yang Lebih Besar
Pada 11 Maret 2025, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang “Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi”, pemerintah akhirnya memenuhi tuntutan ojol. Walaupun, besaran BHR (kata lain dari THR) hanya 20% dari rata-rata pendapatan per bulan selama 12 bulan terakhir.
Besaran 20% ini jauh dari tuntutan awal gerakan pengemudi dan kurir online yaitu sebesar 100% dari rata-rata pendapatan per bulan atau 1 kali upah minimum. Selain itu, Surat Edaran Menaker ini memiliki celah lain, di antaranya tidak adanya mekanisme sanksi bagi platform yang menolak membayar BHR pengemudi atau kurirnya; dan frasa “produktif dan berkinerja baik” dalam poin 3 dalam Surat Edaran Menaker dapat digunakan perusahaan platform untuk menerapkan kriteria tertentu untuk memperoleh BHR, sehingga dapat membuat banyak pengemudi dan kurir online menjadi dikecualikan sebagai penerima BHR karena dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut.
Dipenuhinya tuntutan THR untuk ojol ini, bukanlah semata-mata hasil dari niat baik pemerintah atau platform digital, tetapi lebih merupakan buah dari tekanan kolektif yang terus dilakukan oleh organisasi/serikat pengemudi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam konteks kebijakan publik, tekanan dari bawah (bottom-up pressure) merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong perubahan regulasi, terutama ketika tekanan tersebut dilakukan secara terorganisir dan dalam skala besar.
Teori kebijakan publik seperti Multiple Streams Framework menjelaskan bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika tiga elemen utama bertemu: masalah (problem stream), solusi kebijakan (policy stream), dan momentum politik (political stream). Dalam kasus tuntutan THR bagi ojol, problem stream sudah jelas: pengemudi gig berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan ketenagakerjaan. Policy stream mulai berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja gig. Namun, yang paling menentukan adalah political stream, yaitu seberapa besar tekanan politik yang muncul untuk mendorong perubahan.
Tekanan kolektif dari serikat pekerja ojol menjadi faktor yang dapat mengubah keseimbangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi-aksi protes ojol semakin meningkat, mulai dari mogok kerja hingga demonstrasi besar di berbagai kota. Pada Maret 2020 sampai Maret 2022, ada 71 aksi protes yang dilakukan oleh pengemudi ojol. Protes semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga dapat memaksa pemerintah untuk merespon, baik melalui dialog sosial maupun intervensi kebijakan.
Dalam konteks global, gerakan pekerja gig juga telah berhasil mendorong perubahan regulasi di beberapa negara. Di Inggris, kasus Uber vs Aslam (2021) di Mahkamah Agung menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa pengemudi Uber berhak atas hak-hak ketenagakerjaan dasar, termasuk upah minimum dan tunjangan. Keputusan ini bukan terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari bertahun-tahun perjuangan di jalur hukum dan tekanan kolektif dari serikat pekerja.
Oleh karena itu, dipenuhinya tuntutan THR untuk ojol di Indonesia (walaupun tidak 100%), ini perlu dilihat sebagai kemenangan kecil yang dapat membuka jalan bagi kemenangan yang lebih besar—yakni, pengakuan penuh terhadap hak-hak ketenagakerjaan bagi pekerja gig. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa hak-hak pekerja tidak pernah diberikan secara cuma-cuma oleh negara atau perusahaan, melainkan diperoleh melalui perjuangan kolektif dan negosiasi yang berkelanjutan.
Subscribe to our newsletter!
*Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

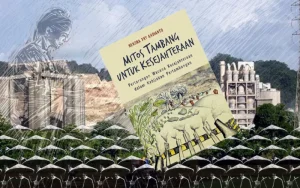








Sangat membantu driver apabila THR turun,meskipun aplikator memaksa untuk narik per trip tetapi jika hujan pasti driver tidak narik itu yg jadi kendala di jalanan,
Harusnya aplikator lebih paham apa itu THR/BHR jadi janganlah kau persulit driver mu dengan Ferforma,Trip,rating.
Jadi kalau bisa semua merata dapat menikmati THR/BHR,
Khususnya untuk Negara harus tegas atau memaksa aplikator untuk memberikan THR/BHR karena kasihan rakyat Indonesia tidak sejahtera