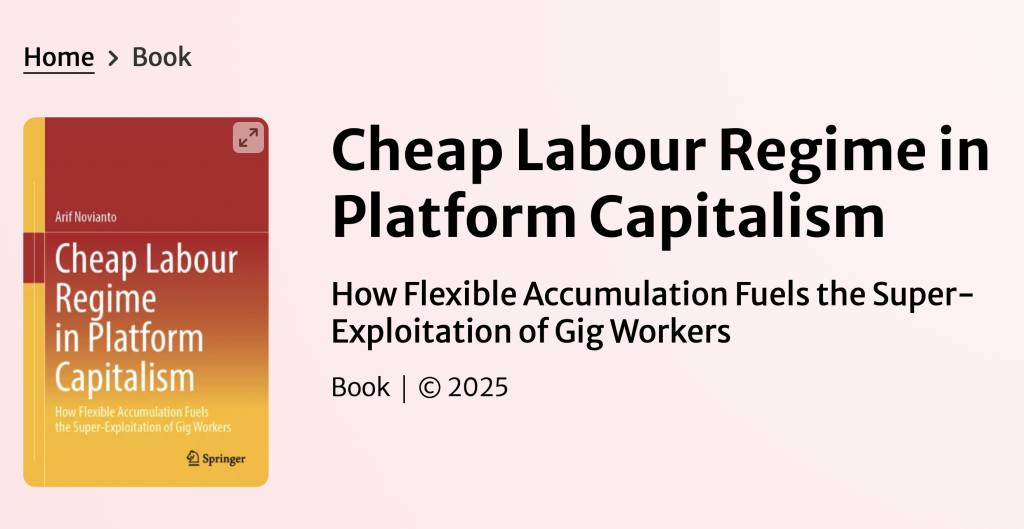Sejak ekonomi gig berkembang pesat di Indonesia, khususnya di sektor transportasi online, status hukum para pengemudi Gojek, Grab, dan Maxim terus menjadi perdebatan. Di awal kemunculannya, status sebagai mitra atau independent contractor dianggap sebagai bentuk relasi kerja yang modern, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi digital. Namun, pada perkembangannya, status sebagai mitra mulai banyak dipertanyakan.
Berdasarkan survei yang saya dan tim lakukan (2020-2024), menunjukkan bahwa semakin banyak pengemudi online yang menginginkan status mereka diubah menjadi pekerja platform, dengan hak dan perlindungan sebagaimana yang didapat pekerja formal.
Perubahan Persepsi tentang Kemitraan
Sebelum pandemi Covid-19, sebagian besar pengemudi online di Indonesia masih merasa bahwa kemitraan yang mereka jalani dengan platform tidak terlalu bermasalah. Survei Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 86% pengemudi online roda 2 menganggap hubungan kemitraan yang mereka jalani “cukup adil”, “adil”, dan “sangat adil”. Sedangkan hanya 14% pengemudi ojol merasa hubungan kemitraan di Gojek “semena-mena” dan “sangat semena-mena”.
Saat itu, kebijakan bakar-bakar uang (money-burning), berupa insentif tinggi bagi pengemudi serta diskon besar-besaran bagi konsumen, berdampak pada peningkatan pendapatan pengemudi. Pada tahun 2018, rata-rata pendapatan kotor pengemudi online yang menggunakan mobil adalah 581.892 rupiah/hari dan pengemudi motor sebesar 315.713 rupiah/hari.
Selain itu, fleksibilitas waktu dan kebebasan dalam memilih orderan dipandang sebagai keunggulan dalam ekonomi gig. Narasi mengenai fleksibilitas dan otonomi kerja yang dikampanyekan oleh platform membentuk persepsi bahwa pekerjaan di platform digital menawarkan kebebasan yang sulit ditemukan dalam pekerjaan formal.
Insentif yang relatif tinggi, fleksibilitas, dan otonomi kerja pada praktiknya berfungsi sebagai “obat sesaat” bagi pengemudi dalam menghadapi kerentanan akibat skema kemitraan yang bersifat semu. Hal tersebut memberikan efek menenangkan sementara, sehingga pengemudi cenderung mengabaikan risiko dan ketidakpastian dalam hubungan kemitraan. Alhasil, selama periode bakar-bakar uang, persepsi terhadap kemitraan menjadi lebih positif karena keuntungan finansial dan keleluasaan kerja tampak lebih menonjol dibandingkan aspek kerentanannya.
Setelah berakhirnya era bulan madu (honeymoon period) atau bakar-bakar uang, pendapatan pengemudi turun drastis dan fleksibilitas serta otonomi yang diperoleh mulai menghilang. Dampaknya, sebagaimana survei yang saya dan tim lakukan di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) UGM pada tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam persepsi pengemudi tentang kemitraan. Sebanyak 53,1% pengemudi online pada tahun 2020 menyatakan lebih memilih status sebagai pekerja platform dibanding mitra.
Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana survei terbaru kami (dalam proses terbit) memperlihatkan bahwa 58% pengemudi online menyatakan lebih setuju jika status mereka diubah menjadi pekerja dibanding sebagai mitra. Pergeseran ini menunjukkan adanya kesadaran kritis yang berkembang di kalangan driver, yang mulai mempertanyakan keadilan substantif dan persoalan fleksibilitas dalam hubungan kemitraan di Gojek, Grab, Maxim, dan InDriver.
Tabel 01. Persepsi Pengemudi Online tentang Status Kemitraan dan Pekerja dari Tahun ke Tahun
| Tahun | Persentase Driver yang Setuju Status Kemitraan | Persentase Driver yang Setuju Status Pekerja |
|---|---|---|
| 2018 | 86% | – |
| 2020 | 46,9% | 53,1% |
| 2024 | 42% | 58% |
Sumber: data pada tahun 2018 dari Lembaga Demografi UI (2018) dengan berdasarkan jawaban pengemudi yang menyatakan bahwa kemitraan yang mereka alami bersifat “cukup adil”, “adil” dan “sangat adil” sebanyak 86% dan jawaban “semena-mena” dan “sangat semena-mena” sebanyak 14%; data pada tahun 2020 dari penelitian yang saya dan tim lakukan berjudul “Di Balik Kendali Aplikasi”; data pada tahun 2024 dari penelitian yang saya dan tim lakukan berjudul “Bisnis Baru, Bentuk Eksploitasi Lama”.
Ilusi Fleksibilitas dan Logika Algoritma
Ekonomi gig selama ini mempromosikan fleksibilitas sebagai nilai jual utama. Pekerja gig dianggap memiliki kebebasan penuh mengatur waktu kerja, memilih pesanan, hingga mengatur strategi pendapatan sendiri. Namun, studi-studi terbaru mengungkapkan bahwa fleksibilitas ini hanyalah ilusi. Algoritma platform justru menciptakan kontrol terselubung yang sangat ketat terhadap perilaku kerja driver.
Pengemudi online yang tidak mencapai target order atau sering menolak pesanan, secara otomatis dikenai penalti algoritmik—berupa penurunan performa atau skorsing akun sementara. Kondisi ini mendorong pengemudi bekerja jauh lebih panjang dari standar jam kerja normal demi mengejar pendapatan atau insentif yang terus berubah sesuai kepentingan platform. Fleksibilitas yang dijanjikan platform, dalam konteks ini, berubah menjadi fleksibilitas sepihak yang merugikan pekerja.
Status mitra juga berimplikasi pada hilangnya perlindungan hukum yang seharusnya dinikmati pekerja. Sebagai mitra atau kontraktor independen, pengemudi tidak mendapat upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan kesehatan, atau hak atas cuti dan pesangon. Ketika terjadi pemutusan kemitraan sepihak, driver juga tidak memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil karena mereka tidak diakui sebagai pekerja.
Kontrak kemitraan yang sepenuhnya disusun oleh platform menciptakan relasi kuasa yang timpang. Di satu sisi, driver dibebani risiko bisnis yang besar, mulai dari biaya kendaraan, perawatan, bensin, hingga risiko kecelakaan kerja. Di sisi lain, platform meraup keuntungan dari komisi transaksi, tanpa perlu menanggung kewajiban sebagai pemberi kerja.
Hegemoni Fleksibilitas: Ketakutan dan Realitas Pekerjaan Formal
Meski kesadaran kritis di kalangan driver terus berkembang, narasi fleksibilitas masih menjadi hegemoni yang sulit dipatahkan. Sebagian driver tetap mempertahankan status kemitraan karena menganggap fleksibilitas sebagai keunggulan utama. Namun, di balik itu, terdapat ketakutan tersembunyi bahwa perubahan status menjadi pekerja formal dikhawatirkan akan membuat mereka tidak memenuhi syarat administratif—seperti batas usia maksimal, tingkat pendidikan, atau persyaratan administratif lainnya.
Ketakutan ini beralasan, mengingat mayoritas driver online berusia di atas 31 tahun dan memiliki latar pendidikan SMA atau lebih rendah. Dalam banyak skema rekrutmen formal di Indonesia, usia dan pendidikan menjadi filter utama, yang bisa membuat sebagian besar driver terdepak dari sistem ketenagakerjaan formal. Ketidakpastian inilah yang menjadikan sebagian driver enggan mendukung perubahan status dari mitra menjadi pekerja. Namun, jika berkaca dari kasus perubahan klasifikasi pengemudi Uber di Inggris, diskriminasi berdasarkan usia dan pendidikan tidak terjadi, karena semua driver Uber diubah statusnya tidak lagi sebagai mitra.
Selain faktor administratif, terdapat pula persoalan struktural dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia: upah minimum yang rendah dan belum mencapai living wage. Di Yogyakarta, misalnya, upah minimum tahun 2024 sebesar Rp2.124.170 masih jauh di bawah estimasi kebutuhan hidup layak sebesar Rp4,13 juta per bulan. Bagi sebagian pengemudi online, meski pendapatan harian sebagai mitra tidak pasti, dalam kondisi tertentu mereka masih bisa meraih pendapatan harian lebih tinggi dibanding upah minimum formal, walaupun harus melakukan eksploitasi-diri.
Kombinasi hegemoni fleksibilitas, ketakutan administratif, dan kelemahan struktural upah minimum di Indonesia inilah yang menjadikan sebagian driver tetap mendukung status kemitraan. Mereka terjebak dalam paradoks: di satu sisi, mereka menyadari eksploitatifnya sistem kemitraan, tetapi di sisi lain mereka takut terhadap ketidakpastian yang menyertai status pekerja formal.
Penutup
Fenomena pergeseran persepsi driver online dari mitra menuju pekerja menandai lahirnya kesadaran baru di tengah ekonomi gig Indonesia. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya tuntas karena dihadang oleh realitas struktural ketenagakerjaan Indonesia yang masih rapuh. Regulasi yang berkeadilan perlu diperjuangkan tidak hanya untuk mengoreksi ketimpangan relasi kuasa dalam ekonomi gig, tetapi juga memperbaiki kualitas ketenagakerjaan formal agar lebih layak dan manusiawi.
Subscribe website ini dengan cara memasukkan email Anda pada form di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan informasi dari arifnovianto.id
*Foto: Katadata/Fauza Syahputera